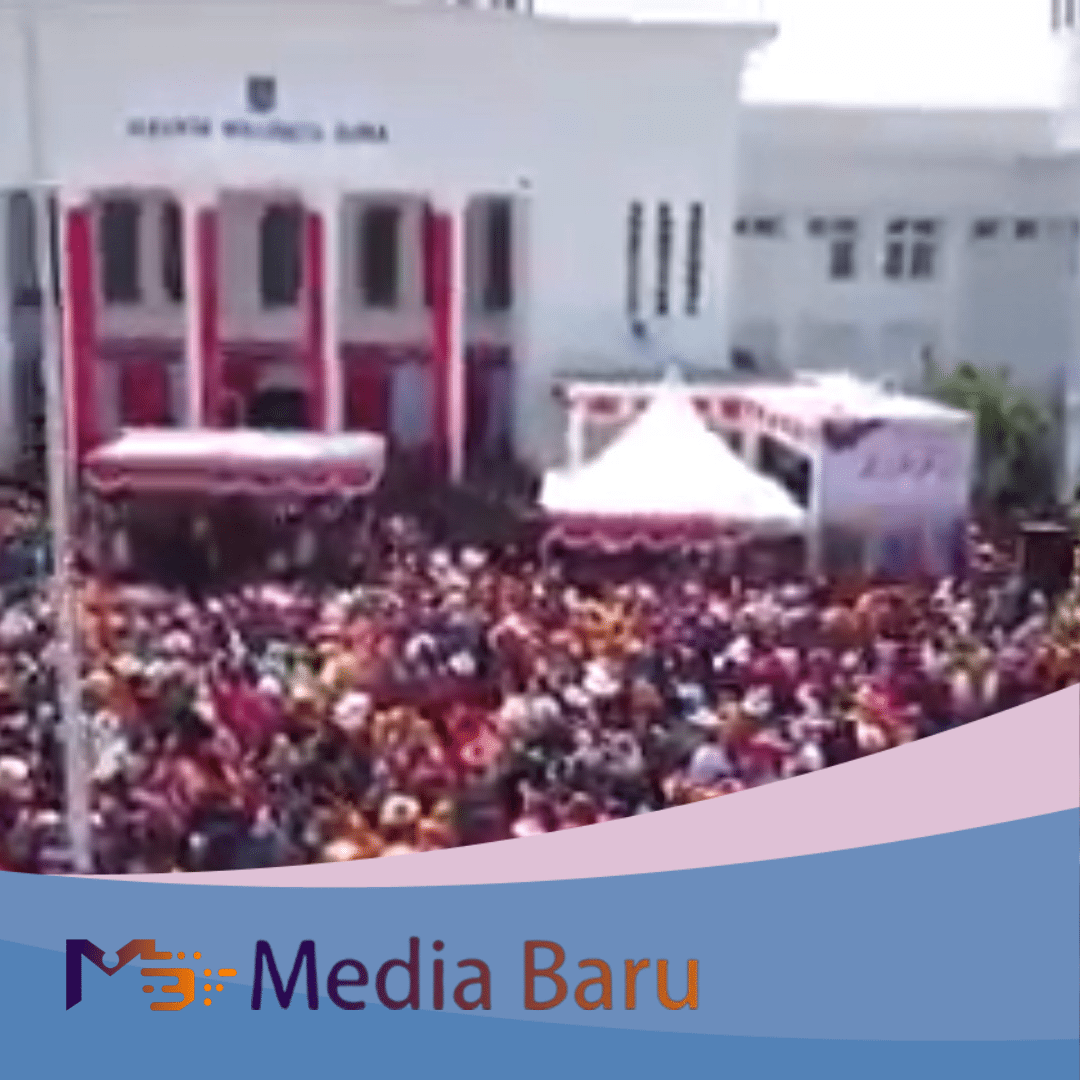Penyimpangan yang Berawal dari Rekor MURI
Festival Rimpu telah menjadi salah satu ajang kebanggaan masyarakat Bima dan Dompu dalam merayakan identitas budaya. Tradisi ini pertama kali mencatat sejarah pada 1 April 2015, ketika Kabupaten Dompu berhasil meraih rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan 13.009 peserta yang mengenakan Rimpu secara massal. Keberhasilan ini kemudian diperbarui pada 1 April 2017, ketika jumlah peserta meningkat pesat hingga 27.111 orang, menjadikannya salah satu festival budaya terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Euforia perayaan budaya ini kemudian diikuti oleh Kota Bima yang menggelar Festival Rimpu pada 12 Oktober 2019. Dengan partisipasi 20.165 peserta, Kota Bima kembali mencetak sejarah dengan memperoleh rekor MURI dalam kategori serupa. Antusiasme yang luar biasa ini menunjukkan bahwa Rimpu bukan sekadar pakaian adat, tetapi juga simbol identitas yang terus dijaga oleh masyarakat Bima dan Dompu.
Pergeseran Pakem Pemakaian Rimpu dan Sambolo

Di tengah gemerlap pencapaian rekor dan kebanggaan akan tradisi, terjadi fenomena yang mengundang diskusi: pergeseran pakem pemakaian Rimpu oleh kaum wanita serta penggunaan Sambolo bagi pria. Dalam budaya asli, Rimpu memiliki dua bentuk utama—Rimpu Colo dan Rimpu Mpida—masing-masing dengan makna dan tata cara pemakaian yang khas. Namun, dalam Festival Pawai Rimpu dan kegiatan bertemakan Rimpu lain beberapa tahun terakhir, muncul modifikasi yang perlahan-lahan menggeser kaidah pemakaian yang diwariskan oleh leluhur.
Selain itu, terdapat inovasi baru seperti Saremba Tembe, yakni kain sarung yang diselempangkan di satu bahu. Padahal, dalam tradisi masyarakat Bima lama, tidak ada perpaduan antara pemakaian Sambolo dengan Saremba Tembe tersebut. Bahkan, dalam pakaian adat laki-laki, sarung atau kain kedua tidak dikenakan sebagai saremba di bahi melainkan sebagai ikat pinggang atau salempe. Ikat pinggang ini bisa menggunakan weri dan dalam kehidupan keseharian masyarakatnya juga bisa menggunakan sarung.

Pergeseran juga terlihat dalam bentuk Sambolo yang dikenakan dalam Festival Rimpu. Dalam tradisi asli Bima, Sambolo memiliki ciri khas tersendiri, di mana bagian runcingnya tidak dibiarkan menjulang ke atas seperti ikat kepala khas Sumatra, melainkan dilipat ke bawah samping kiri atau kanan. Hanya bagian belakangnya yang dibiarkan meruncing pada salah satu bagian ikatannya. Namun, dalam Festival Rimpu, bentuk Sambolo yang digunakan lebih menyerupai ikat kepala Sumatra, yang bagian depannya dibuat mengerucut ke atas, menciptakan tampilan yang berbeda dari pakem asli Sambolo Bima.
Pemerintah sebagai Pionir dalam Pemajuan Kebudayaan

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar sebagai pionir dalam pemajuan kebudayaan. Mengingat Festival Rimpu di Kota Bima diinisiasi dan dibiayai oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran negara, maka seharusnya pemerintah juga memiliki peran aktif dalam menjaga keaslian budaya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa pemerintah justru menggunakan anggaran negara untuk menghapus adat dan budaya Bima dan menggantinya dengan modifikasi yang tidak sesuai dengan pakem tradisional.
Sebagai solusi, pemerintah dapat mengambil langkah konkret dengan memanggil para budayawan sepuh untuk memberikan contoh langsung mengenai tata cara berpakaian adat Bima yang benar. Dokumentasi dari para budayawan ini kemudian dapat dijadikan pedoman resmi dan disosialisasikan kepada para peserta Festival Rimpu. Langkah ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan, terutama karena 90% peserta Pawai Rimpu merupakan pegawai pemerintah, yang seharusnya bisa lebih mudah diarahkan dalam pelestarian budaya yang autentik.
Festival Rimpu, Antara Dinamika Budaya dan Pelestarian Tradisi

Budaya memang bersifat dinamis dan berkembang sesuai zaman, tetapi tanpa batasan yang jelas, kita bisa kehilangan nilai-nilai otentik yang telah diwariskan selama berabad-abad. Festival Rimpu harus tetap menjadi kebanggaan, bukan hanya karena jumlah pesertanya yang memecahkan rekor atau karena masuk dalam event nasional, tetapi juga karena kemampuannya menjaga kemurnian budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
Masyarakat Bima dan Dompu perlu berdialog lebih dalam mengenai arah perkembangan Festival Rimpu. Apakah festival ini akan terus berkembang sebagai ajang pelestarian budaya, atau justru bergeser menjadi sekadar pertunjukan massal yang kehilangan akar tradisionalnya? Jawaban atas pertanyaan ini ada di tangan kita semua sebagai pewaris budaya yang bertanggung jawab.
Redaksi Media Baru